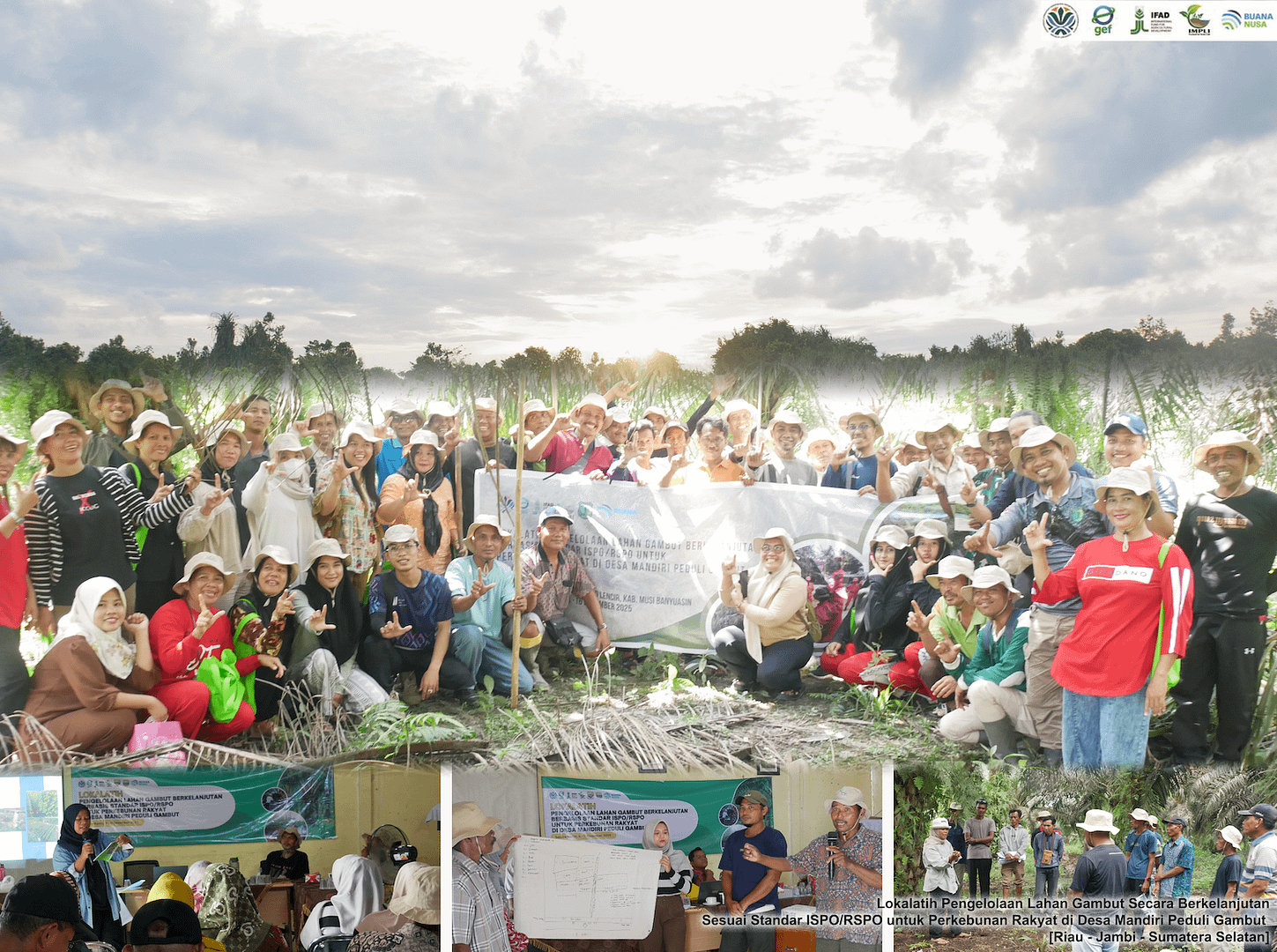Mengapa sertifikasi sawit sering tersendat bukan di kebun, melainkan pada infrastruktur pembuktian: data, peta, dan jejak rantai pasok.
Oleh: subrantas
Di banyak desa sentra sawit, ada adegan yang berulang. Seorang pekebun kecil datang ke pertemuan kelompok, mendengarkan fasilitator menjelaskan pentingnya sertifikasi. Ia mengangguk – ia ingin kebunnya tertib, aman, dan akses pasarnya stabil.
Tetapi begitu pembicaraan bergeser dari niat baik ke pembuktian, ruang mendadak sunyi: STDB sudah ada? Bukti penguasaan lahan apa? Batas kebun sudah dipetakan? Koordinatnya titik atau poligon? Catatan panen dan input ada?
Di titik itu, kita melihat masalah sebenarnya. Sertifikasi sering macet bukan karena orang menolak menjadi berkelanjutan, tetapi karena sistem meminta bukti yang belum siap. Ini bukan perkara moral. Ini perkara desain tata kelola: standar dinaikkan, sementara jembatan untuk mencapainya dibiarkan setengah jadi.
Sertifikasi pada dasarnya audit bukti
Publik kerap mengira sertifikasi adalah pemeriksaan praktik budidaya. Praktik memang penting, tetapi yang paling menentukan dalam audit adalah evidence: apakah klaim bisa diverifikasi, bisa ditelusuri, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, sertifikasi adalah audit terhadap bukti – bukan sekadar audit kebun.
Di era due diligence, sawit bukan hanya komoditas fisik. Sawit adalah komoditas plus metadata: asal-usul, status risiko, jejak rantai pasok, dan audit trail. Jika metadata itu tidak rapi, maka komoditas sebaik apa pun akan sulit masuk ke ruang yang menuntut kepastian.
Di Indonesia, prasyarat bukti itu hadir juga dalam rezim domestik. Untuk pekebun, dokumen dasar seperti STDB dan bukti penguasaan lahan sering menjadi pintu awal yang harus dilewati. Ketika pintu awal saja macet, proses sertifikasi berhenti sebelum auditor datang.
Ilusi tanpa biaya: audit bisa dibantu, bukti tetap harus dibangun
Banyak program menyampaikan sertifikasi sebagai sesuatu yang dibantu, difasilitasi, bahkan terdengar tanpa biaya. Yang jarang dibicarakan: biaya terbesar justru muncul sebelum audit – biaya membangun paket bukti.
Biaya ini sering tidak muncul di proposal, tidak tercatat di kuitansi, namun nyata dalam jam kerja lapangan. Paket bukti mencakup enumerasi dan verifikasi kebun, pemetaan geospasial (titik dan poligon) dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, pembenahan dokumen penguasaan lahan, serta sistem pencatatan operasional yang rutin. Lalu ada lapisan yang makin penting: tata kelola data – siapa menyimpan, siapa mengakses, dan bagaimana memperbaiki kesalahan.
Jika infrastruktur pembuktian tidak dibangun sebagai komponen inti, biaya itu akan jatuh sebagai biaya tersembunyi ke pihak yang paling lemah: pekebun, pengurus kelompok, atau fasilitator. Di sinilah sertifikasi bisa bergeser dari instrumen perbaikan menjadi mekanisme eksklusi yang halus.
Beban bukti naik kelas: geolokasi presisi dan risiko pencampuran
Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan pasar bergerak cepat menuju pembuktian yang lebih presisi. Salah satu pemicunya adalah rezim deforestation-free dan kewajiban uji tuntas di sejumlah pasar, termasuk Eropa. Bagi rantai pasok, ini berarti geolokasi bukan formalitas; ia menjadi dasar untuk menilai risiko.
Untuk sawit, persoalan berikutnya lebih rumit: pencampuran (mixing). Komoditas bulk mudah bercampur di titik pengumpulan, pengepul, dan logistik. Namun tuntutan pembuktian cenderung mengarah pada satu pesan: asal-usul harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika rantai pasok tidak mampu menjelaskan dari mana komoditas berasal dan bagaimana risiko dikendalikan, akses pasar akan tersendat.
Di sini ketimpangan terlihat jelas. Komoditasnya fungible – mudah dipindahkan dan dicampur. Tetapi buktinya non-fungible – spesifik pada plot, spesifik pada dokumen, spesifik pada jejak. Ketika jembatan pembuktiannya rapuh, standar baru mudah berubah menjadi pagar tinggi.
Sepuluh titik macet yang menjatuhkan sertifikasi
Masalah sertifikasi bisa dibaca lebih jernih jika kita melihat proses sebagai rangkaian titik kontrol. Dari pengalaman programatik, ada sepuluh titik macet yang paling sering menjatuhkan kesiapan: (1) identitas pekebun dan data kebun tidak konsisten; (2) batas kebun kabur atau tumpang tindih; (3) registrasi kebun belum terbit atau tidak terverifikasi; (4) dokumen penguasaan lahan tidak defensible; (5) geolokasi tidak memenuhi format atau mutu; (6) catatan operasional kosong; (7) dokumen lingkungan minimum tidak lengkap; (8) sistem kontrol internal ada di kertas, tetapi tidak hidup; (9) rantai pasok tidak mampu menjelaskan risiko pencampuran; (10) tata kelola data tidak jelas.
Perhatikan: mayoritas adalah problem data, dokumentasi, dan tata kelola – bukan problem agronomi. Artinya, solusi yang hanya menambah sosialisasi kepatuhan tidak akan menyentuh akar masalah.
Solusi realistis: Minimum Viable Evidence dan layanan bersama
Jika diagnosisnya adalah bukti tidak siap, maka resepnya adalah rekayasa sistem pembuktian. Dua langkah paling masuk akal adalah Minimum Viable Evidence (MVE) dan layanan bersama (shared services).
MVE berarti paket bukti minimum yang membuat proses bisa berjalan, lalu ditingkatkan bertahap. Misalnya: identitas pekebun tervalidasi, poligon kebun yang memenuhi standar dasar, dokumen penguasaan lahan minimum yang dapat dipertanggungjawabkan, format pencatatan operasional yang sederhana, dan mekanisme koreksi data.
Shared services berarti kita berhenti mengharapkan pekebun menjadi ahli GIS dan ahli arsip sekaligus. Di tingkat koperasi atau yurisdiksi, layanan bersama dapat menurunkan biaya: unit pemetaan kolektif dengan SOP dan QA/QC, enumerator terlatih, repositori data dengan kontrol akses, serta pendampingan sistem kontrol internal yang fokus pada audit trail, bukan dokumen pajangan.
Kuncinya satu: kurangi beban bukti pada pihak yang paling lemah tanpa menurunkan integritas. Bagi rantai pasok, investasi pada bukti bukan hanya bantuan sosial; ia mitigasi risiko yang jauh lebih murah daripada krisis kepatuhan.
Penutup
Kita perlu mengakhiri narasi yang menyalahkan niat petani atau menyederhanakan masalah menjadi sekadar kurang sosialisasi. Banyak pekebun ingin tertib. Yang membuat mereka tersendat adalah pembuktian yang menuntut data, peta, dan jejak yang belum tersedia secara sistemik.
Jika bukti adalah tiket masuk pasar berkelanjutan, maka kesiapan bukti adalah kebijakan inklusi. Selama bukti dianggap urusan tambahan, sertifikasi akan terus macet. Bukan niatnya yang salah. Cara kita menyiapkan bukti yang harus dibenahi.