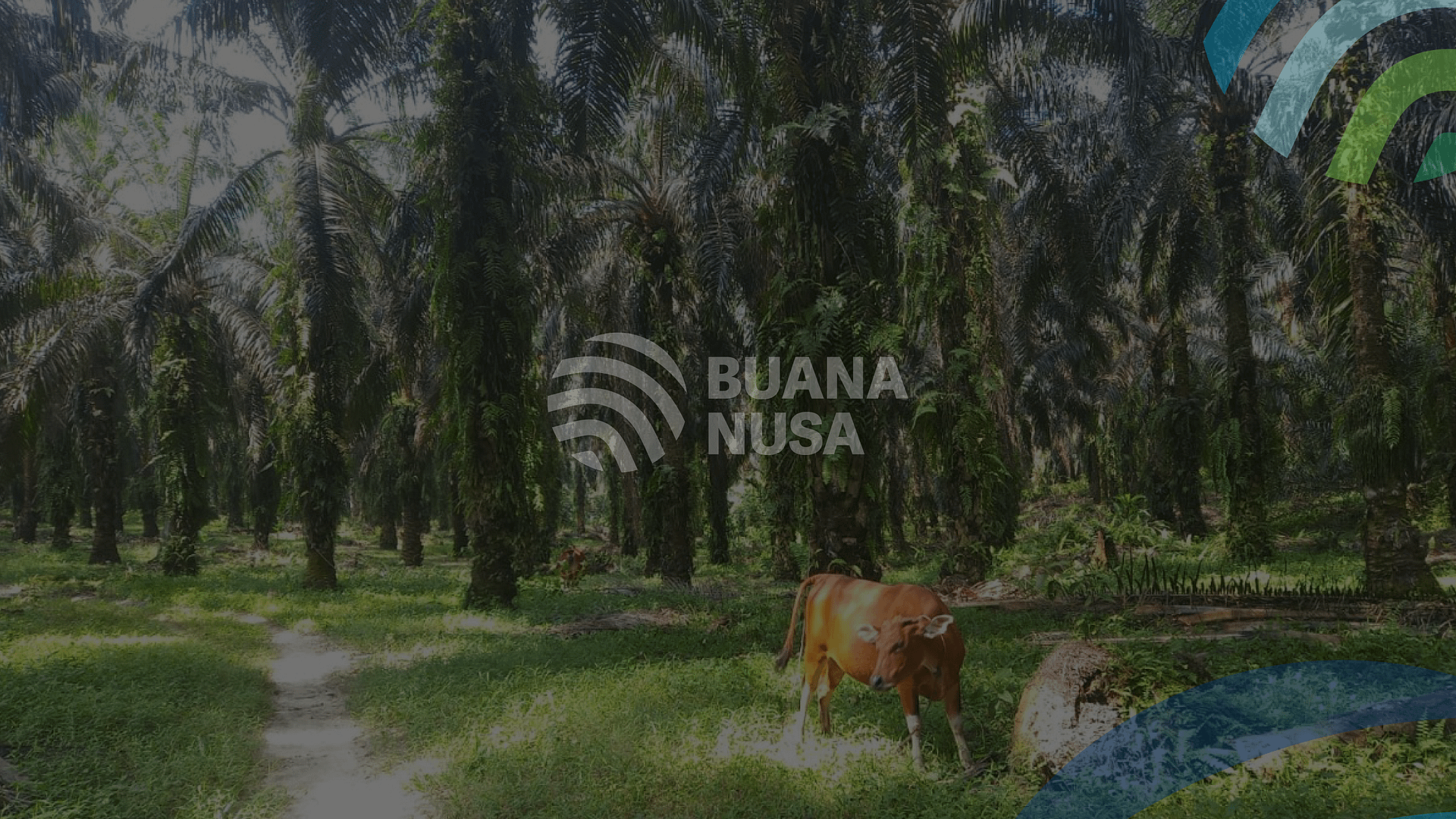Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sedang berada di persimpangan antara ambisi ekonomi dan tuntutan keberlanjutan global. Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) menjadi instrumen kunci untuk menjawab tekanan pasar internasional, terutama Uni Eropa yang memberlakukan EU Deforestation Regulation (EUDR) 2023. Namun, di balik upaya memperkuat daya saing ekspor, tersembunyi paradoks: bagaimana memastikan 2,8 juta petani sawit skala kecil—yang menguasai 41% total lahan sawit nasional—tidak terperangkap dalam ketidakadilan sistemik? Di tengah komitmen global menuju net-zero emission, ISPO 2025 diuji bukan hanya sebagai alat sertifikasi, tetapi sebagai cerminan keadilan transisi ekologis di tingkat tapak.

Data Kementerian Pertanian (2023) mengungkap ironi pahit: hanya 0,5% petani swadaya tersertifikasi ISPO. Biaya sertifikasi Rp 2,3 juta per hektare—setara dengan 6 bulan pendapatan petani rata-rata—menjadi tembok tak terjangkau. Masalahnya tidak sekadar finansial. Sekitar 60% kebun rakyat (3,4 juta hektare) belum bersertifikat tanah, tumpang tindih dengan kawasan hutan, atau masuk wilayah adat. Tanpa kepastian hukum, upaya sertifikasi berisiko mengkriminalisasi petani yang dianggap “ilegal” oleh sistem. Sementara itu, perusahaan besar dengan akses modal dan teknologi telah mengantongi 89% sertifikat ISPO, memperlebar jurang ketimpangan dalam rantai pasok sawit.
ISPO tidak boleh direduksi menjadi alat komodifikasi pasar global. Di tingkat nasional, ia harus menjadi jalan resolusi konflik agraria kronis—tercatat 196 sengketa lahan terkait sawit (2022) oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Sertifikasi yang mengabaikan aspek keadilan hanya akan menjadi green exclusion: petani kecil yang tidak mampu memenuhi standar dokumen akan tersingkir, sementara korporasi dengan lahan “legal” terus mendominasi. Di tataran global, kritik terhadap ISPO sebagai greenwashing semakin nyata. Uni Eropa, misalnya, masih meragukan ISPO karena dianggap kurang ketat dalam perlindungan HAM dan hutan primer. Jika ISPO gagal mengintegrasikan dimensi keadilan, Indonesia berisiko kehilangan legitimasi di mata dunia sekaligus mengorbankan petaninya sendiri.
Agar ISPO 2025 tidak menjadi “elite capture”, diperlukan intervensi struktural. Pertama, pemerintah harus membiayai sertifikasi petani kecil melalui APBN atau dana pungutan ekspor sawit. Model sertifikasi kelompok—seperti di Malaysia (MSPO)—bisa diadopsi untuk menekan biaya. Kedua, percepat penerbitan sertifikat tanah melalui program Reforma Agraria, dengan prioritas bagi kebun rakyat yang tumpang tindih kawasan hutan (*in-between lands*). Ketiga, koperasi petani perlu diperkuat sebagai mitra setara perusahaan dalam hal akses teknologi, pembiayaan, dan pasar. Keempat, libatkan organisasi petani dan LSM dalam proses sertifikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
ISPO 2025 akan gagal jika hanya menjadi alat kompromi politik antara tekanan Uni Eropa dan lobi korporasi sawit. Keberlanjutan sejati harus dibangun dari bawah. Standar ISPO harus menyerap kearifan lokal petani, seperti sistem agroforestri sawit-berbasis biodiversitas, bukan mengekor standar Barat. Kriteria sertifikasi perlu memasukkan indikator pengurangan kemiskinan, upah layak, dan partisipasi perempuan. Di forum global, Indonesia harus lebih vokal menentang kebijakan diskriminatif Eropa sekaligus menunjukkan komitmen inklusivitas ISPO.
Pada akhirnya, masa depan sawit berkelanjutan Indonesia ditentukan oleh kemampuannya menjadikan petani kecil sebagai subjek—bukan objek—dari transisi hijau. Tanpa ini, ISPO hanyalah sertifikat tanpa jiwa. Konflik lahan di Kalimantan dan Sumatera, dominasi korporasi, serta ketimpangan ekonomi petani kecil (25% hidup di bawah garis kemiskinan/BPS 2023) harus menjadi prioritas. Di tengah persaingan dengan Malaysia (MSPO) dan kritik LSM internasional, Indonesia perlu membuktikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar label, melainkan janji keadilan bagi manusia dan alam.